Dunia Keruh Islamofobia
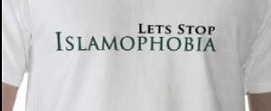
Dengan semua propaganda kebencian terhadap Islam yang ditiupkan media Barat, kita mungkin tergoda untuk bertanya ada apa dengan Barat? Kenapa mereka begitu cemas dengan Islam? Ini pertanyaan besar yang perlu penjelasan. Tapi jaringan teve ABC di Amerika Serikat telah memotret fenomena itu secara khusus, dalam kehidupan masyarakat pecinta senjata di Texas, dan membawanya ke layar kaca pada 2006.
Tokohnya adalah Nohayia Javed, remaja perempuan Muslim kelahiran Chicago, Amerika. Seperti ribuan Muslim di Amerika lainnya, dia sering dicemooh. Lahir dan besar di Chicago, Javed seringkali dicemooh orang di jalan-jalan. Kadang, cemoohan itu berkembang hingga menjadi penyerangan fisik. Pangkalnya bukan karena dia pernah merampok Federel Reserve Bank of Chicago, tapi semata-mata karena dia adalah Muslimah yang berjilbab.
“Mereka biasanya langsung mendamprat begini, ‘Hai teroris! Fans Osama (bin Laden)! Perempuan bertudung handuk! Penunggang onta’ dan lain-lain,” kata Javed mengenang. "Jika saya katakan bahwa saya adalah warga Amerika, mereka membalas, ‘Bukan, kau bukan orang Amerika. Hanya karena kau lahir di sini tidak menjadikanmu orang Amerika'. Dalam hati saya sering membatin:‘Lalu apa yang membuatmu jadi orang Amerika?’”
Tergerak dari cerita Javed itu, ABC merancang sebuah liputan. Mereka merencang sebuah reka ulang untuk memeriksa sejauh mana kesahihan laporan Javed.
Untuk hasil otentik, kru ABC memasang kamera tersembunyi di semua sudut toko roti The Czech Stop yang berada di Waco, negara bagian Texas. Dua aktor dipasang di dalam toko. Pertama adalah manajer toko yang menolak menjual roti dan menghardik dengan kecaman anti Islam dan anti Arab. Aktor lain adalah wanita berhijab yang hendak membeli roti.
Hasilnya mengejutkan.
Sabina, wanita yang memerankan posisi Javed, mula-mula memasuki toko roti untuk membeli strudel apel. Di kasir, laki-laki lain yang berperan sebagai manajer bergegas menyambutnya dengan kata-kata penuh kebencian atas pelanggan berhijab itu.
“Pergi dari sini!" katanya membentak. "Cari saja onta dan kembali ke tempat asalmu. Bawa itu handuk di kepalamu. Apa sih maumu? Apa sih yang ada di balik belitanmu itu? Pergi dari sini dan cari roti di tempat lain!”
“Tuan," kata Sabina memelas, "saya ini adalah warga Amerika seperti tuan. Saya lahir dan besar di sini.”
Para pelanggan lain yang hadir di lokasi dengan jelas mendengar kata-kata kasar yang dilontarkan oleh sang manajer. Tapi, tak satu pun yang peduli.
Dan Sabina tak berhenti mengiba ke pengunjung yang datang untuk membantu membeli strudel apel. "Tuan," katanya lagi, "sudikah Anda membelikan strudel apel untuk saya?"
Meski terlihat kaget dengan kata-kata kasar si manajer, seorang pengunjung setengah baya hanya menatap Sabina dingin. Kikuk, dia mengambil uang Sabina, membeli strudel dan bergegas keluar.
Di luar, seorang anggota kru ABC berpura-pura menanyakan kericuhan di dalam toko roti. Orang yang kita kira bersimpati itu malah berkata, “Saya pikir sebaiknya seorang manajer boleh memilih untuk menjual barang kepada siapa saja yang dimauinya.”
Ironis. Rasisme seperti ini masih kental meski hukum di Amerika Serikat sejak 1964 mengharuskan pemilik toko yang menjual barang dagangan umum tidak boleh menolak melayani pelanggan karena alasan suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal-usul kebangsaannya.
Tapi pria setengah baya itu bukan satu-satunya pelanggan toko roti yang membela “hak” sang manajer untuk melakukan diskriminasi. Beberapa orang lain yang menyaksikan langsung adegan itu bahkan spontan mendukung langkahnya menghardik konsumen berjilbab.
Beberapa saat kemudian, Sabina kembali masuk ke toko roti yang sama. Dan lagi-lagi manajer toko menolak untuk melayaninya. Kata-kata kasar serupa pun berhamburan keluar dari mulut si manajer. Adegan hampir sama berulang.
Bedanya, kali ini ada seseorang yang langsung bangun dan melakukan pembelaan. Tapi lacurnya, pihak yang dia bela bukannya pelanggan Muslimah yang berhijab, tapi si manajer yang sedang uring-uringan itu. Dengan santai, dia mendekati kasir dan menyapa. “Dia (Sabina) tidak berpakaian yang layak,” katanya, “Kalau saya yang mengelola tempat ini, saya juga pasti bersikap sama dengan Anda.”
Yang lebih mengejutkan, saat Sabina keluar toko dengan kecewa dan tangan hampa, satu orang lain mengucapkan terima kasih pada si manajer toko roti. Tidak cukup, si pemuda gagah itu bahkan mengacungkan dua jempolnya berbarengan sebagai tanda salut.
Saat semua adegan itu direkam, Javed mengamati dari dalam van milik ABC. Dia ternganga, bingung dengan reaksi orang yang apatis. “Saya terkejut," katanya, "karena saat hal-hal ini saya alami dalam dunia nyata … Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah saya meninggalkan sebuah toko dan sebagainya."
“Adakalanya saya mencari-cari justifikasi … bahwa mereka mungkin tidak dengar. Namun, kini, setelah saya melihat reka ulang ini, saya sadar bahwa mereka sebenarnya mendengar dan melihat sekaligus merasa okey dengan semua itu.”
Namun, menjelang akhir film, saat ada dua pengungjung toko yang maju membela Sabina, Javed tampak meneteskan airmata. Kegusarannya sejak awal bercampur dengan airmata keriangan. Dia berterima kasih pada mereka yang datang membela Sabina. “Seumur hidup saya, tidak pernah ada seorang pun yang berdiri membela,” kata Javed. “Sangat menyentuh melihat orang-orang yang mau mengambil risiko untuk membela yang lemah. Dan saya percaya itulah hal benar yang harus dilakukan orang Amerika.”
Javed ternyata tidak sendirian. Dan mungkin orang-orang selain Javed hanya bisa meneteskan airmata kegusaran. Dari data FBI kita tahu bahwa angka kejahatan anti-Islam berlipat ganda dalam depalan tahun terakhir. Pada tahun 2000, angkanya ‘baru’ 28 kali. Enam tahun kemudian, jumlahnya mencapai 156 kali dalam setahun. Angka ini sepertinya terus meningkat, seiring meningkatnya angka kematian tentara AS yang berperang di Irak dan Afganistan.
Di akhir tayangan, ABC mewawancarai Jack Dovidio, psikolog sosial jebolan Yale University. Dovidio menyatakan bahwa orang-orang semacam itu tampaknya mendefinisikan “orang Amerika” berdasarkan penampilan luarnya. Mereka merasa dekat dengan manajer dan menganggap orang berhijab sebagai orang luar (outsider). “Tatkala kita sebagai warga Amerika merasa ada ancaman dari luar, kita cenderung mengidentifikasi diri secara kaku,” kata Dovidio. “Kau bersamaku atau musuhku. Atau, jika kau tidak benar-benar sama denganku, maka kau pasti adalah musuhku.”
Diskriminasi atas Nohayia Javed ternyata hanya percikan api dalam sekam yang lebih besar. Kebencian dan ketakutan tak berdasar, yang lazim disebut dengan Islamofobia itu, berdentang keras di seantero Amerika sejak Tragedi 11 September. Sekiranya bukan karena liputan media, yang dalam banyak hal terus memanipulasi keadaan, pastilah peristiwa itu akan dikenang seperti umumnya tragedi kemanusiaan lain. Bahkan mungkin saja bisa memperkuat solidaritas dan simpati umat manusia.
Apa hendak dikata! Media massa, dan korporasi di belakangnya, punya niat busuk untuk memupuk kebencian dan paranoia masyarakat Amerika. Tujuan mereka tentu untuk menundukkan opini publik dan memobilisasinya demi agenda politik jangka pendek mereka sendiri.
Sejak beberapa bulan terakhir ini, bola api “Islamofobia” masuk ke arena perebutan tiket menuju Gedung Putih. Kubu politisi berkulit hitam Barack “Hussein” Obama sempat gusar bukan alang kepalang kala rival-rivalnya mempertautkannya dengan Islam. Untuk menarik kembali simpati yang mungkin hilang, kubu Obama berkali-kali memberikan klarifikasi bahwa Obama adalah warga Kriten yang taat beragama. Obama sendiri bahkan menunjukkan bahwa dia juga tidak kalah keras dalam sentimen anti-Islamnya.
Penulis Inggris yang memenangkan Hadiah Nobel untuk kategori sastra, Doris Lessing, melihat lebih jauh. Akibat label “Islam” atau “asing” yang melekat pada Obama, Lessing yakin Obama bakal dibunuh seperti J.F. Kennedy jika benar-benar terpilih sebagai presiden. “Dia mungkin tidak akan bertahan lama sebagai president kulit hitam di AS. Mereka akan membunuhnya,” tandas Lessing dalam wawancaranya dengan sebuah koran Swedia.
Upaya Mengurai Benang Kusut
Airmata kegusaran adalah airmata sebagian besar umat Islam, terutama setelah kita melihat fenomena Islamofobia menyebar seperti virus di daratan Eropa. Eropa sejak lama dipandang sebagai sumbu toleransi Islam di Barat, surga harapan puluhan juta imigran Muslim dari negara-negara yang terbabit konflik.
Citra positif Eropa memancar dari berbagai kebijakan luar negerinya. Dalam kasus Palestina, umpamanya, Eropa sering berseberangan dengan Israel/Amerika. Rakyat Eropa pada umumnya juga menolak invasi Irak. Puluhan juta warga tumpah ke jalan-jalan London, Paris, Madrid, Berlin, Roma dan ibukota-ibukota Eropa lain sejak genderang perang ditabuh kaum Neokonservatif di Washington dan Downing Street, Inggris. Mereka jelas-jelas menolak konfrontasi militer untuk menyelesaikan sengketa apapun dengan dunia Islam.
Semua ini tentu saja membantu jutaan imigran Muslim di Eropa untuk merasa nyaman dengan sistem dan budaya setempat. Timesonline sekali waktu memuat hasil survei The Gallup yang intinya menegaskan asumsi di atas. Warga Muslim London, misalnya, lebih senang menyebut dirinya sebagai orang Inggris ketimbang umumnya warga entis lain. Ia juga menyebut 57% Muslim di Inggris mengidentifikasi diri mereka dengan Inggris sebagai negara dibanding 48% sisa populasi etnis lain.
Survei juga mengisyaratkan bahwa 74% Muslim merasa setia pada Inggris dan 78% Muslim menyatakan kepercayaan mereka pada polisi Inggris, jauh melampaui seluruh responden populasi lain. Survei itu kemudian memperlihatkan bahwa 67% Muslim percaya pada sistem hukum Inggris dan 73% yakin dengan proses demokrasi di Inggris. Sementara sisa populasi yang disurvei hanya mendapat 55% dan 60% dalam masing-masing poin pertanyaan.
Sialnya, sejak invasi Irak, Al-Qaedah merangsek ke Eropa. Berbagai bom bunuh diri berdentaman di sejumlah ibukota benua itu. Dari London sampai Madrid, aksi-aksi picik Al-Qaedah memunculkan borok lama di tubuh Barat. Bau busuk Islamofobia pun menyebar dari benua ini. Bedanya: kali ini dengan sengatan yang lebih menusuk.
Orang bisa bilang bahwa Islamofobia di Eropa adalah reaksi atas terorisme Al-Qaedah. Namun, kita tidak bisa melupakan bahwa Al-Qaedah hanya perlu membalik tangan untuk mempertegas mispersepsi lawas ihwal Islam di tengah masyarakat Eropa: ”kita” lawan ”mereka”.
Di negeri Belanda, Geert Wilders hanya perlu manipulasi sederhana atas tewasnya produser film Theo van Gogh tahun 2004 di Amsterdam untuk masuk ke dunia parlemen Belanda. Masyarakat Belanda yang memendam mispersepsi lama tentang Islam melihat tewasnya van Gogh sebagai momentum penting untuk meradikalisasi pandangan mereka atas Islam. Wilders, politikus muda bermulut naga ini, tahu betul manfaat tewasnya van Gogh bagi karir politiknya.
Kurt Westergaard dan Flemming Rose, redaktur budaya koran Jyllands-Posten, yang punya hubungan karib dengan Daniel Pipes (tangki pemikir neokon), juga tahu betul ihwal memori kolektif Eropa yang berisi miskonsepsi mengenai Islam. Begitu Jyllands-Posten memasang rangkain kartun karya Westergaard tentang Nabi Muhammad saw, yang mendapat tentangan keras dari dunia Islam, miskonsepsi itu dengan cepat berubah menjadi Islamofobia stadium empat. Dalam kartun itu, Nabi Suci Muhammad, tambatan hati 1,4 milyar umat Islam, ditampilkan sebagai lelaki yang parasnya seperti begal dan bersorban dinamit.
Flemming berdalih kartun itu untuk “menghangatkan perdebatan” seputar kritik atas Islam di Barat. Tapi jelas sekali bahwa alasan bodoh itu hanya untuk memancing tawa satwa liar. Kritik dan sarkasme adalah dua kata yang saling bertentangan di kamus orang waras.
Bagi kelompok ultranasionalis di Eropa, kemarahan umat Muslim yang memprotes pemuatan kartun Nabi itu adalah amunisi tambahan untuk mempertentangkan Islam dan Eropa. Saat luka ratusan juta umat Muslim masih belum kering, atas nama solidaritas kebebasan pers, tidak kurang dari 50 media Barat berbarengan memuat kartun yang sama.
Selanjutnya, media massa Eropa pun keranjingan menampilkan dua wajah kontras “Islam”—entah Islam yang seperti apa. Di satu sisi, ada orang-orang eks-Muslim seperti Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan, Magdi Allam dan sejenisnya; di sisi lain, kita disuguhi pesan-pesan kebencian dari Osama bin Laden dan Ayman Al-Zawahiri. Obsesi ini jelas masuk dalam skenario segelitir petualang politik di Eropa. Sebuah kontras yang tidak menggambarkan mayoritas Muslim, apalagi Islam yang sebenarnya.
Trend itu terus meningkat. Kini, orang-orang murtad langganan tampil di media Barat untuk menjelaskan Islam—tentu saja Islam ala al-Qaedah, Taliban dan sejenisnya. Ini jelas lawakan murahan untuk ukuran semua orang! Tapi, rupa-rupanya, rangkain pengeruhan akal sehat itu makin memperteguh miskonsepsi tentang Islam di benak masyarakat Eropa umumnya.
Bagi Muslimin manapun, manipulasi di atas sebetulnya mirip dengan usaha Don Alfonso, tokoh dalam opera Mozart Cosi fan tutte. Bahwa semua masyarakat membenci Islam, dan bahwa semua orang Islam adalah Al-Qaedah, Taliban dan kelompok garis keras pembunuh berdarah dingin, pemerkosa perempuan, penikmat seks dengan anak-anak, pembunuh wartawan dan sebagainya.
Kita sadar bahwa masyarakat Barat secara umum jauh dari sifat monolitik. Namun, sial majal, upaya kelompok ultranasionalis-neokonservatif mengubah Barat menjadi monolit raksasa lamat-lamat menunjukkan hasil. Kalau tidak segera dipecah, skenario benturan Islam-Barat bisa menjadi ancaman serius sebentar lagi.
Di sisi umat Islam, saran seorang kolumnis The Guardian, Ali Eteraz, untuk meniru Hossein Nouri dalam memprotes rasanya terlalu mengawang. (Hossein Nouri adalah pelukis lumpuh asal Iran yang menggambar potret Maryam, ibunda Isa Al-Masih, di depan kedutaan besar Denmark saat demo memprotes publikasi kartun-kartun yang menghina Nabi di Tehran tanggal 13 Februari 2006). Pasalnya, jelas tidak semua orang Muslim bisa melukis seindah Nouri, pun tidak semua orang Barat mengerti bahasa artistik dalam lukisan.
Kita memang harus tetap memprotes. Berteriak lantang, merentang spanduk-spanduk yang menyatakan kemarahan. Terutama kita harus memprotes penyalahgunaan isu-isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi untuk menodai kesucian Nabi dan al-Qur’an.
Tapi semua itu juga tidak memadai. Salah satu cara melawan pembentukan monolit Islamofobia di Barat adalah dengan melihat konteks kemunculannya secara lebih luas. Bahwa Islamofobia di Barat jelas bukan sebuah fenomena baru. Ia penyakit kambuhan yang kemunculannya dilatari beragam faktor.
Lepas dari faktor sejarah, merebaknya miskonsepsi ihwal Islam yang tidak terjawab secara rasional dan relevan jelas ikut memperuncing konflik. Kita tidak sedang berbicara tentang jawaban-jawaban apologetik emosional ala orator setengah matang di mimbar-mimbar mesjid; jawaban yang, lacurnya, justru hanya menunjukkan bahwa kita adalah umat yang kekurangan gizi intelektual. Yang kita perlukan adalah jawaban-jawaban filosofis dan dialogis yang matang, mendalam, autentik dan penuh kepercayaan. ****
Oleh : Musa Khazim (http://ahlulbaitindonesia.org)
Kirim komentar