Menghargai Ragam Kecerdasan Anak
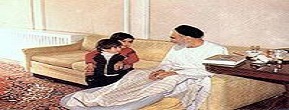
kecerdasanMari kita bandingkan antara Aristoteles dengan Thomas Alpha Edison. Aristoteles adalah filosof besar, yang sampai hari ini, karyanya terus dipelajari di seluruh dunia. Ia menulis tentang fisika, metafisika, logika, matematika, politik dan juga etika. Banyak pemikirannya yang menjadi teori besar, tetapi, sepanjang hidupnya, tidak ada satupun penemuan (teknologi) yang dibuat Aristoteles. Di sisi lain, Thomas Alpha Edison, adalah penemu (alat-alat teknologi) paling banyak di dunia (diperkirakan mencapai 300 temuan). Ia tidak banyak menulis buku, tapi ia banyak membuat alat. Ia bekerja dengan barang-barang yang ada disekitarnya dan meramu serta membuat berbagai temuan yang sangat bermanfaat bagi dunia, seperti bola lampu. Tetapi, tahukah Anda, Edison pernah mengeluh, karena saat membaca buku yang ditulis oleh Aristoteles, tidak ada satupun yang dapat ia pahami. Pertanyaannya, siapakah yang paling cerdas di antara mereka : Aristoteles atau Thomas Alpha Edison? Jawabnya : ‘keduanya sama-sama cerdas!’
Memang, “Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah perbedaan model kecerdasan yang dimiliki anak”, begitulah kira-kira yang dapat kita simpulkan, dari teori Multiple Intellegence (Kecerdasan Majemuk) yang dikembangkan oleh Howard Gardner.
Kita mungkin sering mengira bahwa anak yang jago dalam studi matematika dan bahasa adalah anak yang cerdas, dan yang tidak jago dalam pelajaran tersebut kita golongkan sebagai anak yang kurang cerdas (bodoh). Lihatlah UN (Ujian Nasional) hanya diberlakukan bagi empat bidang pelajaran yang jika kita cermati hanya difokuskan pada dua bidang kecerdasan, yaitu logis-matematika dan bahasa.
Padahal, menurut Howard Gardner, manusia memiliki Kecerdasan Majemuk, dan Gardner telah menemukan delapan kecerdasan manusia, sebagai berikut :
Kecerdasan Linguistik (Bahasa) yaitu senang terhadap makna dan susunan kata : menulis cerita dan esai; bercerita lucu, plesetan, kisah; memiliki kosakata yang luas; bermain kata (word game).
Kecerdasan Logis-Matematis (Logika-Matematika) yaitu kemampuan dalam argumentasi serta mengenali pola dan urutan, Bekerja dengan angka, memecahkan masalah, menganalisis situasi, memahami kerja sesuatu.
Kecerdasan Musikal (Musik) yakni senang terhadap irama, nada, dan nyanyian: Mendengarkan dan bermain musik; menyesuaikan perasaan dengan musik, bernyanyi, mencipta dan meniru lagu.
Kecerdasan Spasial yakni kemampuan untuk mengindera sesuatu dengan akurat dan menciptakan kembali apa yang diindera tersebut : mencoret-coret, melukis atau menggambar; mebuat peta dan diagram; visualisasi; membongkar dan menyusun.
Kecerdasan Naturalis (Alam) yang mampu mengenali dan mengklasifikasi aneka spesies, flora dan fauna dalam lingkungan : suka di luar ruangan; mengumpulkan tanaman, bebatuan, binatang; mendengarkan bunyi-bunyi di alam; memperhatikan hubungan alam semesta.
Kecerdasan Kinestesis Tubuh yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh dengan terampil : Berolah raga dan aktif secara fisik; berani ambil risiko dengan tubuh mereka; menari, bermain peran, dan meniru gerak; bermain dengan benda mekanis.
Kecerdasan Interpersonal yaitu kemampuan untuk memahami orang dan membina hubungan : Senang berteman banyak; memimpin, berbagi, menengahi; membuat kesepakatan; membantu teman yang bermasalah; menjadi anggota tim yang efektif.
Kecerdasan Intrapersonal yakni akses pada kehidupan emosional diri sebagai sarana untuk memahami diri sendiri dan orang lain: Merenung; mengendalikan perasaan dan suasana hati sendiri; mengejar minat pribadi dan menyusun agenda; belajar dengan mengamati dan mendengarkan; menggunakan kecakapan metakognitif.
Dengan mengetahui kedelapan kecerdasan ini, sistem pendidikan harus dipola untuk mengenal dan menggali kecerdasan anak sehingga dapat membimbing mereka menuju kesuksesan yang sesuai dengan kepribadiannya. Karenanya, guru tidak layak lagi beranggapan negatif dengan melihat siswa-siswanya dari satu kacamata ukuran kecerdasan.
Boleh saja anak yang tidak jago matematika (kecerdasan logis), namun berhasil dalam mengarang dan menjadi penulis handal (memiliki kecerdasan bahasa). Guru juga mungkin sulit berkomunikasi dengan anak pemalu dan pendiam, namun jago berkhayal sehingga menjadi arsitek yang dapat membangun gedung pencakar langit (memiliki kecerdasan spasial); atau menjadi penyair dan musisi yang sukses (memiliki kecerdasan musik).
Guru mungkin sering bertemu siswa ‘nakal’ yang menjengkelkan karena suka teriak dan bergerak kesana kemari, karena memang ia juara dalam berolah raga (memiliki kecerdasan kinestetik), atau hal itu bisa saja terjadi karena model belajar yang sangat membosankan. Guru mungkin senang dengan anak pendiam yang mudah diatur (memiliki kecerdasan intrapersonal) daripada anak yang tidak bisa duduk tenang di kursinya walau hanya satu menit saja, tapi guru jangan lupa, anak yang memiliki kecerdasan interpersonal memang ‘susah diatur’, sebab ia memiliki jiwa pengatur/pemimpin (memiliki kecerdasan interpersonal).
Secara fisiologis, kata Danah Zohar, koneksi saraflah yang memberi kita kecerdasan. Seorang bayi terlahir dengan kebutuhan utama untuk mempertahankan hidup—pada tahap ini koneksi-koneksi saraf untuk mengatur pernafasan, detak jantung, suhu tubuh, dan lain-lain. Akan tetapi, seorang bayi belum dapat melihat wajah dan benda, membentuk konsep, atau menyuarakan bunyi yang bermakna. Kemampuan-kemampuan semacam ini berkembang sejalan dengan waktu : melalui kontak dengan dunia, otak membangun jaringan saraf baru. Semakin kaya dan beragam pengalaman yang diterima olehnya, semakin kompleks dan besar koneksi saraf yang terbentuk. Itulah sebabnya kita dapat menumbuhkembangkan kecerdasan anak-anak, termasuk koordinasi fisiknya, dengan memberi mereka rangsangan atau stimulasi secara berulang-ulang dan bervariasi—seperti benda-benda berwarna cerah untuk dilihat, berbagai bunyi dan suara untuk didengar, berbagai benda untuk dicium dan dirasakan, usapan lembut di punggung atau di kepala, dan dekapan emosional yang hangat. Semakin dewasa, koneksi saraf yang baru itu memberi anak-anak kemampuan berbahasa dan pembentukan konsep. Koneksi-koneksi ini menyimpan fakta dan pengalaman memori, memungkinkan mereka membaca, menulis, dan melakukan pembelajaran secara luas. Tidak ada batasan dalam hal jumlah dan kompleksitas koneksi saraf yang dapat ditubuhkan pada otak seorang anak. Karenanya, kita harus melakukan perubahan dan pembuatan aturan secara kreatif sehingga dapat terus memperbaharui ulang otak kita sepanjang hidup.
Dengan memahami kompleksitas dan koneksi saraf otak, kita dapat mengetahui bahwa berpikir bukanlah proses otak semata-mata atau bukan urusan IQ saja. Kita berpikir tidak hanya dengan otak, tetapi juga dengan emosi dan tubuh (EQ), serta dengan semangat, visi, harapan, kesadaran akan makna, dan nilai kita (SQ). IQ merupakan berpikir seri dengan sistem sebab-akibat : jika x maka y, rasional, dan ilmu pasti. Yang digunakan adalah jalur saraf (neural tracts). Sedangkan EQ adalah berpikir asosiatif : melihat kemungkinan, mencari hubungan seperti lapar-nasi, emosional, mengenal gambar, wajah, aroma, belajar keterampilan gerak, berpikir dengan menggunakan hati dan tubuh. Yang digunakan adalah jaringan saraf (neural network). Adapun SQ merupakan berpikir unitif yang menggabungkan beripkir IQ dan EQ, yang mengunakan otak, hati, dan tubuh.
Jadi, teori multiple intellegence Howard Gardner telah membantu siswa untuk mengenal bakat dan kecerdasannya. Kemudian juga, teori ini telah merubah pandangan guru terhadap siswa dan sistem pendidikan yang monokultural. Artinya, Kita harus memanfaatkan semua potensi anak, baik indera, tubuh, akal, ataupun hatinya dengan memberikan kebebasannya untuk mengembangkan bakat dan minat mereka dalam suasana yang kondusif dan efektif. Ada anak yang mampu mengerjakan soal matematika setelah dibiarkan menyanyi atau bermain gitar, begitu pula ada anak yang bisa mengarang jika ia berada di alam terbuka sambil menikmati kicau burung dan suara alam. Untuk itu, anak tidak hanya diajar mendengar guru, tetapi juga haeus berbicara, bergerak, bertindak, dan berbuat. Pepatah cina mengatakan : “Saya mendengar dan saya lupa; Saya melihat dan saya ingat; Saya melakukan dan saya mengerti”. Dr. Vernon Magnesen dari Universitas Texas meneliti kemampuan ingatan manusia saat belajar dengan cara : membaca (hanya 20 % yang diingat), mendengar (30 %) , melihat (40 %), mengucapkan (50 %), dan melakukan (60 %). Dan jika menggabungkan semuanya yakni “mendengar, melihat, mengucapkan, dan melakukan hasilnya adalah 90 % dapat diingat.
Melalui penelitian Dr. Vernon Magnesen ini kita diberitahukan bahwa jika kita ingin anak-anak kita belajar dengan sebaik-baiknya, bukanlah dengan menghapalnya tetapi melakukannya. Suruhlah anak-anak melakukan semua yang dipelajarinya, maka ia akan ingat sepanjang hayatnya. Jangan hanya suruh anak-anak menghapal bacaan salat, tetapi suruhlah mereka melaksanakan salat, sehingga ia akan hapal dengan sendirinya. [tvshia/liputanislam.com]
Kirim komentar